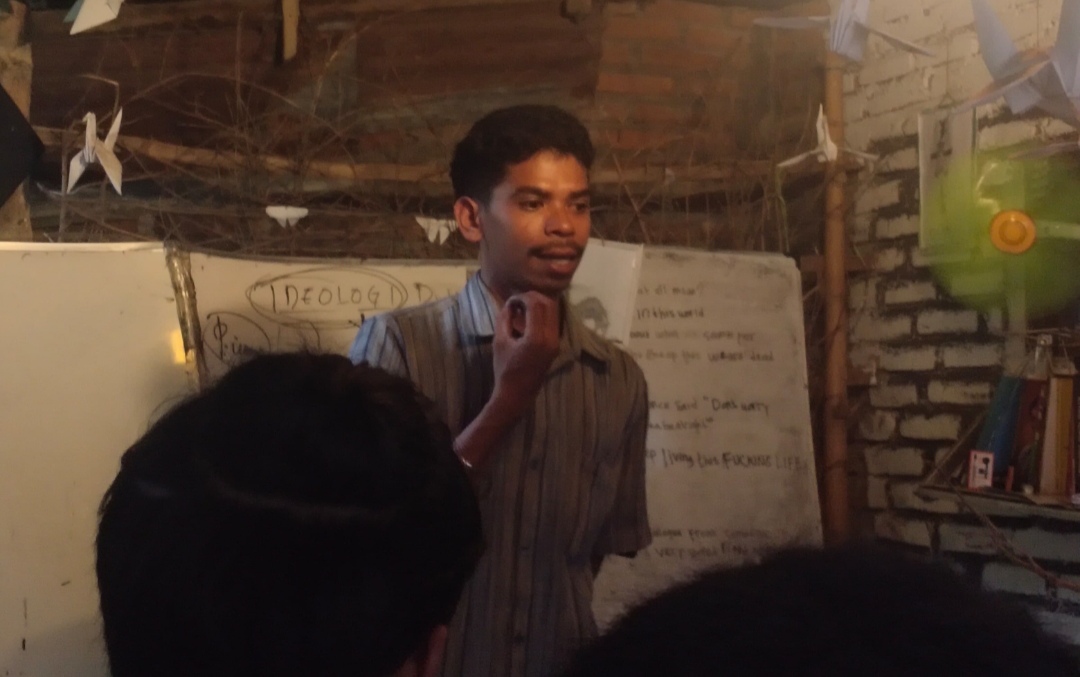Puasa: Menghancurkan Tembok-tembok yang Memisahkan
Penulis : Gunawan Hatmin
Puasa, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah yang bersifat personal, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam. Secara esensial, puasa berfungsi sebagai alat untuk menghancurkan “tembok-tembok” yang memisahkan manusia dari Allah SWT dan sesamanya.
Tembok-tembok ini dapat berupa ego, keserakahan, ketidakpedulian, atau bahkan keangkuhan spiritual yang sering kali menghalangi manusia untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta dan solidaritas dengan sesama. Dalam konteks ini, puasa menjadi sebuah mekanisme transformatif yang mengajak manusia untuk merefleksikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan memperkuat ikatan sosial. Puasa dapat dilihat sebagai bentuk disiplin diri yang melatih manusia untuk mengatasi dorongan-dorongan primitifnya.
Menurut Muhammad Abduh, seorang reformis Muslim abad ke-19, puasa adalah sarana untuk mencapai “tazkiyatun nafs” (penyucian jiwa). Abduh menekankan bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari segala bentuk perilaku yang merusak hubungan dengan Allah dan manusia. Dengan demikian, puasa menjadi alat untuk menghancurkan tembok egoisme dan individualisme yang sering kali menjadi sumber konflik sosial.
Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 183 menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” Ayat ini tidak hanya menegaskan kewajiban puasa, tetapi juga menjelaskan tujuannya, yaitu mencapai ketakwaan. Takwa, dalam konteks ini, adalah keadaan di mana manusia menyadari keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga ia mampu menghancurkan tembok-tembok yang memisahkannya dari Sang Pencipta. Takwa juga mengimplikasikan kesadaran sosial, di mana seorang yang bertakwa akan senantiasa peduli terhadap nasib sesamanya.
Kuntowijoyo, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, menambahkan dimensi sosial dalam pemahaman puasa. Menurutnya, puasa adalah bentuk “protes terhadap ketidakadilan” karena ia mengajarkan manusia untuk merasakan lapar dan dahaga, yang pada gilirannya menumbuhkan empati terhadap kaum miskin dan tertindas. Dengan demikian, puasa tidak hanya menghancurkan tembok antara manusia dan Allah, tetapi juga tembok-tembok sosial yang memisahkan manusia dari sesamanya. Puasa mengajarkan kesetaraan, karena semua orang, kaya atau miskin, merasakan hal yang sama ketika berpuasa.
Mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab juga menekankan bahwa puasa adalah proses “pembebasan diri” dari belenggu materialisme dan hedonisme. Dalam dunia modern yang serba instan dan materialistis, puasa mengajak manusia untuk kembali kepada esensi kehidupan yang sejati, yaitu hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama. Dengan menahan diri dari hal-hal yang halal sekalipun, manusia belajar untuk tidak menjadi budak dari keinginan-keinginan duniawi.
Secara keseluruhan, puasa adalah ibadah yang revolusioner karena ia memiliki kekuatan untuk mentransformasi diri manusia secara individu maupun kolektif. Ia menghancurkan tembok-tembok spiritual yang memisahkan manusia dari Allah, sekaligus tembok-tembok sosial yang memisahkan manusia dari sesamanya.
Melalui puasa, manusia tidak hanya mencapai ketakwaan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil, empatik, dan penuh solidaritas. Sebagaimana dikatakan oleh para filosof dan mufassir, puasa adalah jalan menuju kesempurnaan insani, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai bagian dari umat manusia.